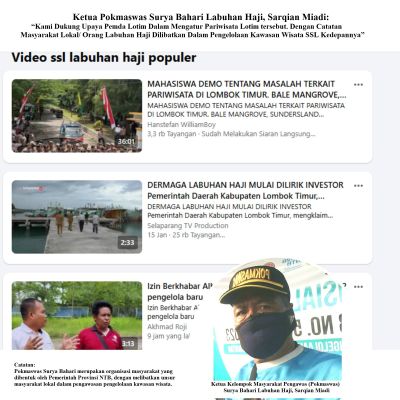Lebih Dekat dan Lebih Terbuka: Gaya Komunikasi Dahnil dan Dinamika Baru Pejabat Publik
Lebih Dekat dan Lebih Terbuka: Gaya Komunikasi Dahnil dan Dinamika Baru Pejabat Publik

Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak berinteraksi dengan calon jemaah haji lansia. Foto: Istimewa
Oleh: Prof. Singgih Tri Sulistiyono
Guru Besar Sejarah, Universitas Diponegoro Semarang
Jakarta (16/2). Antara Seremoni dan Jarak Simbolik. Dalam birokrasi Indonesia, relasi pejabat dan warga kerap dibangun lewat simbol: bahasa resmi yang panjang, istilah teknokratis, tata ruang dan protokol yang berlapis. Kekuasaan tidak hanya tampil sebagai kewenangan administratif, tetapi juga sebagai gestur dan tata acara yang menciptakan wibawa sekaligus jarak.
Pola ini membuat komunikasi publik cenderung satu arah. Kebijakan disampaikan lewat pidato, konferensi pers, atau rilis resmi; masyarakat menjadi penerima, bukan mitra dialog. Aspirasi memang tersedia salurannya, namun sering kali panjang dan formal. Interaksi negara–warga pun lebih menyerupai transmisi pesan daripada percakapan.
Namun lanskap sosial telah berubah. Ruang digital menghadirkan partisipasi yang lebih egaliter dan respons yang serba cepat. Warga bukan lagi pendengar pasif, melainkan aktor yang menuntut keterlibatan. Di titik ini, jarak simbolik yang dulu dianggap wajar mulai dipertanyakan: apakah komunikasi publik cukup berhenti pada seremoni, atau sudah saatnya bertransformasi menjadi dialog yang lebih terbuka dan setara?
Di era digital, komunikasi publik tak lagi berlangsung di “panggung” yang sepenuhnya dikendalikan institusi. Media sosial mengubahnya menjadi ruang cair: percakapan terjadi secara real time, melibatkan banyak aktor, dan meninggalkan jejak yang bisa diuji kapan saja. Jika dulu bahasa birokrasi berdiri seperti tembok yang rapi, resmi, namun berjarak kini tembok itu ditekan dari dua arah: dari atas, pejabat dituntut lebih cepat dan transparan; dari bawah, warga memiliki daya untuk bertanya, mengkritik, bahkan memaksa isu tertentu masuk agenda publik.
Perubahan ini menggeser sumber otoritas. Jabatan tetap penting, tetapi tidak lagi memadai. Di ruang digital, legitimasi lahir dari respons: seberapa sigap menjawab, seberapa jernih menjelaskan, seberapa konsisten bersikap, dan seberapa siap menghadapi pertanyaan yang tak nyaman. Otoritas tak lagi semata kewibawaan formal, melainkan kredibilitas interaksi.
Media sosial memang lebih egaliter secara akses—siapa pun bisa menyanggah, mengoreksi, atau menuntut klarifikasi. Namun ia juga penuh turbulensi: fakta bercampur opini, data berkelindan dengan emosi. Inilah paradoksnya: partisipasi meluas, tetapi kebisingan meningkat.
Dalam situasi ini, pejabat publik menghadapi dilema. Bertahan pada gaya seremonial berarti terlihat jauh; terlalu larut dalam gaya warganet berisiko menggerus wibawa. Yang dibutuhkan bukan sekadar keaktifan, melainkan kecakapan menerjemahkan otoritas ke dalam bahasa yang dipahami public tanpa kehilangan etika dan substansi.
Di titik inilah muncul pendekatan berbeda. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, misalnya, memilih komunikasi yang lebih terbuka dan responsif, menggunakan bahasa yang akrab dengan keseharian warga. Yang menonjol bukan sekadar gaya santai, melainkan pergeseran orientasi: dari seremoni menuju dialog. Ia tak hanya mengumumkan, tetapi juga menanggapi; tak sekadar menyampaikan, tetapi hadir dalam percakapan.
Pendekatan ini mencairkan jarak simbolik yang lazim dalam kultur kepemimpinan. Pejabat tidak lagi berdiri semata sebagai pemegang otoritas, melainkan sebagai partisipan dalam ruang publik. Kritik pun berubah fungsi: dari ancaman yang harus diredam menjadi dialektika yang dapat menguji dan memperkuat kebijakan. Dengan demikian, dinamika yang terjadi bukan hanya soal medium, melainkan transformasi kultur politik.
Ketika bahasa menjadi lebih inklusif dan respons lebih terbuka, negara terasa lebih dekat dan transparan. Ruang digital dengan segala kegaduhannya memaksa negosiasi baru antara kewibawaan dan keterbukaan. Dari sinilah terlihat pergeseran: bukan hilangnya hierarki, melainkan upaya mempertemukannya dengan tuntutan dialog yang tak lagi bisa diabaikan.
Praktik Komunikasi yang Membumi
Dalam konteks tersebut, pendekatan komunikasi yang dipraktikkan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menarik untuk dicermati. Ia tampil dengan gaya komunikasi yang relatif apa adanya, menggunakan bahasa yang ringan dan dekat dengan keseharian warganet. Interaksi digital tidak ia perlakukan sebagai panggung formal birokrasi, melainkan sebagai ruang dialog terbuka. Ia merespons kritik, terlibat dalam perdebatan kebijakan, dan menjawab pertanyaan publik tanpa selalu menggunakan bahasa institusional yang kaku. Pendekatan ini tentu tidak tanpa risiko. Keterbukaan membuatnya rentan terhadap kritik tajam, bahkan serangan personal. Namun justru dalam dinamika itu terlihat bagaimana dialog publik dapat menjadi ruang dialektika yang memperkaya proses pengambilan kebijakan.
Dahnil tampil dengan gaya komunikasi yang apa adanya, bebas, dan tidak kaku. Ia kerap menggunakan bahasa ringan yang dekat dengan keseharian warganet. Pendekatan ini menerabas lintas antropologis—melampaui batas simbolik yang selama ini melekat pada relasi pejabat dan masyarakat—sebagai upaya meruntuhkan tembok hirarkisme dalam komunikasi publik. Interaksi digital tidak ia perlakukan sebagai panggung formal, melainkan ruang dialog terbuka.
Di ruang digital, Dahnil aktif merespons perdebatan kebijakan, termasuk isu penyelenggaraan haji dan umrah. Ia meladeni diskusi dengan gaya percakapan netizen, tanpa jarak bahasa birokrasi yang panjang. Praktik ini berbeda dari kebiasaan sebagian pejabat yang cenderung menjaga komunikasi satu arah melalui pernyataan resmi atau kanal institusional.
Risiko dan Batas Keterbukaan
Keterbukaan dalam ruang digital memang menghadirkan peluang dialog yang lebih egaliter, tetapi ia tidak pernah bebas dari risiko. Media sosial bekerja dalam logika percepatan: informasi menyebar dalam hitungan detik, opini terbentuk sebelum verifikasi selesai, dan emosi sering kali mendahului argumentasi. Dalam situasi seperti ini, pejabat publik yang memilih hadir secara langsung di ruang digital harus siap menghadapi spektrum respons yang sangat luas—mulai dari dukungan, kritik konstruktif, hingga serangan personal yang tidak selalu berbasis data.
Salah satu tantangan utama adalah disinformasi dan simplifikasi isu. Kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan haji dan umrah, memiliki dimensi teknis, administratif, dan diplomatik yang kompleks. Namun ruang digital cenderung mereduksi kompleksitas menjadi narasi singkat yang mudah viral. Dalam konteks ini, keterbukaan menuntut kecakapan menjelaskan persoalan yang rumit dengan bahasa yang sederhana tanpa mengorbankan akurasi. Jika tidak, dialog berubah menjadi arena kesalahpahaman.
Risiko lain adalah erosi wibawa. Dalam kultur birokrasi yang lama, jarak simbolik justru berfungsi menjaga otoritas. Ketika pejabat terlalu cair, terlalu reaktif, atau terjebak dalam perdebatan emosional, kewibawaan bisa terkikis. Di sinilah batas keterbukaan menjadi penting. Komunikasi yang egaliter bukan berarti menanggalkan etika atau larut dalam gaya percakapan yang tidak proporsional. Keterbukaan harus tetap ditopang oleh konsistensi data, ketenangan sikap, dan kontrol diri.
Selain itu, ruang digital juga rentan terhadap polarisasi dan personalisasi isu. Kritik terhadap kebijakan bisa bergeser menjadi serangan terhadap pribadi. Dalam situasi ini, pejabat publik diuji bukan hanya secara argumentatif, tetapi juga secara psikologis. Respons yang terlalu defensif berisiko memperkeruh suasana; respons yang terlalu diam dapat ditafsirkan sebagai pengabaian. Maka diperlukan keseimbangan antara keberanian hadir dan kebijaksanaan untuk memilih kapan merespons dan kapan menahan diri.
Dengan demikian, dinamika baru komunikasi pejabat dan warga tidak dapat dipahami sebagai pergeseran total dari hierarki menuju kebebasan tanpa batas. Ia lebih tepat dibaca sebagai negosiasi berkelanjutan antara otoritas dan partisipasi. Wibawa tidak lagi dibangun melalui jarak, tetapi melalui integritas dan kualitas argumentasi. Keterbukaan bukan berarti meninggalkan struktur, melainkan mengelolanya dalam ruang yang lebih transparan.
Pada akhirnya, ruang digital bukan sekadar arena komunikasi, melainkan ujian etika publik. Pejabat yang memilih hadir secara terbuka harus mampu menjaga substansi kebijakan, ketenangan sikap, dan tanggung jawab moral. Di situlah letak batas sekaligus kekuatan keterbukaan: ia menuntut kedewasaan komunikasi, bukan sekadar keberanian tampil.
Simpulan: Pelajaran bagi Pejabat Publik Indonesia
Catatan ini pada dasarnya bukan hanya tentang satu figur, melainkan tentang perubahan kultur komunikasi negara di era digital. Apa yang diperlihatkan melalui gaya komunikasi yang lebih terbuka menunjukkan bahwa kewibawaan hari ini tidak lagi dibangun semata-mata melalui jarak simbolik, tetapi melalui kualitas interaksi. Jabatan tetap penting, namun legitimasi semakin ditentukan oleh kemampuan menjelaskan, merespons, dan berdialog secara jernih.
Pelajaran pentingnya: keterbukaan bukan kelemahan, selama ditopang oleh etika, akurasi data, dan ketenangan sikap. Kritik di ruang digital tidak selalu ancaman; ia bisa menjadi mekanisme koreksi yang memperkuat kebijakan. Namun keterbukaan juga memerlukan batas agar tidak terjebak dalam polarisasi atau kehilangan wibawa.
Bagi para pejabat Indonesia, tantangannya adalah menemukan keseimbangan baru—mengurangi jarak simbolik tanpa kehilangan integritas struktural. Di era demokrasi digital, negara yang kuat bukanlah yang paling tinggi temboknya, melainkan yang paling jernih komunikasinya dan paling siap hadir dalam dialog.
Editor :Faqihu